Kajian Potensi Komoditas dan Pemasaran pada Areal izin Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Barat dan Riau.
PENGANTAR
Perhutanan Sosial (PS) makin menjadi isu menarik sejak pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kala menjadikannya sebagai program prioritas periode 2014-2019. Menawarkan berbagai skema, izin PS dapat diberikan dalam bentuk pengelolaan Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat (HA).
Meskipun menuai kontroversi, namun kebijakan ini menjadi solusi terbaik ketika berbicara mengenai problem-problem dalam pengelolaan kawasan hutan. Terutama berhubungan dengan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.
Sesuai dengan Nawacita yang diusung Pemerintahan Presiden Jokowi, PS bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar: lahan, kesempatan berusaha dan sumber daya manusia.
Dalam pengertian lainnya PS merupakan perwujudan dari Nawacita, yakni: ke-1 Negara hadir melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia, ke-6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan ke-7, Mewujudkan kemandirian ekonomi dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Masalah kemiskinan dan konflik kehutanan seolah menjadi fenomena laten yang tidak berkesudahan. Kenyataan yang memilukan ini bila ditinjau lebih menyeluruh, tidak bisa dilepaskan dari buruknya pengelolaan kehutanan di era orde baru.
Tonggak mula eksploitasi sumber daya hutan di Indonesia justru bermula setelah Indonesia merdeka. Pada awal masa Soeharto berkuasa, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Sejak itu, banyak korporasi berlomba-lomba mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Dalam periode 1967-1980, Orde Baru Soeharto tercatat menerbitkan 519 HPH dengan luas lahan konsesi sekira 53 juta hektare.
Bisa dikatakan bahwa seluruh kebijakan pemerintah pada saat itu, mulai dari level UU hingga peraturan turunannya selalu menempatkan jutaan jiwa penduduk yang hidup di sekitar kawasan hutan sebagai objek komersialisasi. Masyarakat yang hidup dan bergantung dengan hutan beserta kekayaan yang terkandung di dalamnya belum dijadikan sebagai komponen penting dalam pengelolaan kehutanan.
Alih-alih melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemerintah seolah justru tidak memahami kenyataan bahwa mereka telah eksis atau hidup di sekitar hutan jauh sebelum NKRI berdiri sebagai sebuah negara. Harusnya masyarakat adat perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan pengelolaan dan bahkan implementasinya. Nasib serupa atau bahkan lebih ekstrem dihadapi masyarakat adat.
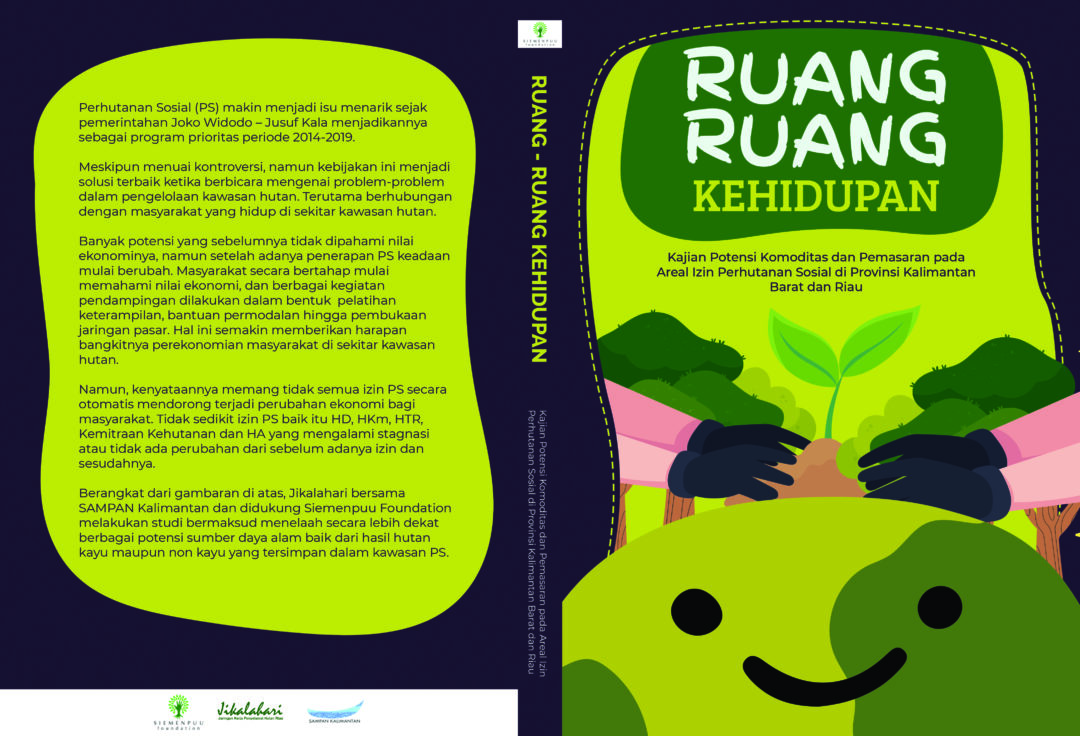
Keberadaanya sebagai masyarakat asli tidak usah diragukan lagi. Sejarah panjang penjelajahan hutan oleh masyarakat adat telah melahirkan tidak hanya ikatan ekonomi dengan hutan beserta kekayaan alam yang ada di dalamnya. Lebih dari itu, hubungan atau ikatan emosional, sosial dan religi lahir dalam kehidupan sosial masyarakat adat dengan hutan.
Apa yang mereka yakini antara hutan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Leluhur mereka telah menyatu ke dalam alam semesta yang harus senantiasa dipuja dan dijaga. Namun, rezim orde baru seolah menutup mata. Bukannya pengakuan seperti yang dimuat pasal 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, justru penjarahan kekayaan hutan oleh korporasi besar datang silih berganti. Keadaan inilah yang sejak awal dan terus menerus makin mempertajam ketimpangan penguasaan hutan.
Pada 2015, perizinan kehutanan untuk korporasi besar mencapai 94 persen, sedangkan untuk masyarakat hanya 4 persen. Perbandingan yang cukup jauh. Sehingga wajar jika penjarahan kekayaan hutan yang terjadi dalam waktu yang cukup panjang tidak memiliki implikasi positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Justru jika membandingkan dengan data angka kemiskinan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan akan membenarkan pepatah ‘tikus mati dilumbung padi’.
Menurut studi Lembaga Penyelidik Ekonomi Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada 2020 menunjukkan, kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan hutan merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Pada akhir 2019, tingkat kemiskinan masyarakat di sektor kehutanan mencapai 20 persen atau terbesar dibandingkan sektor lainnya.
Fenomena kemiskinan akut yang dialami masyarakat di sekitar kawasan hutan memang tidak sesederhana seperti kesimpulan di atas. Banyak aspek yang harus ditinjau untuk dapat menarik kesimpulan akhir penyebab kemiskinan. Salah satunya seperti tingkat pendidikan, keterampilan dan aspek sosial budaya serta keterisolasiannya yang juga menjadi faktor penyerta.
Namun, jika melihat potensi kehutanan indonesia baik hasil hutan kayu maupun non kayu dan termasuk jasa lingkungan yang dihasilkan, rasanya seperti tidak masuk akal jika dihubungkan dengan tingkat kemiskinan yang terjadi.
Oleh karena itu, implementasi PS selama kurang lebih 6 tahun akan menjadi tolok ukur, apakah aspek kepastian hukum mengenai akses masyarakat terhadap kekayaan hutan dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.
Dalam banyak studi, meskipun PS belum sepenuhnya menjawab problem kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan, namun sebuah studi menununjukan bahwa 6 tahun pelaksanaannya, PS telah meletakan dasar yang jauh lebih baik terhadap perkembangan perekonomian masyarakat. Karena adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memanfaatkan atau mengelola potensi kehutanan baik dari hasil hutan kayu maupun non kayu.
Banyak potensi yang sebelumnya tidak dipahami nilai ekonominya, namun setelah adanya penerapan PS keadaan mulai berubah. Masyarakat secara bertahap mulai memahami nilai ekonomi, dan berbagai kegiatan pendampingan yang dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan, bantuan permodalan hingga pembukaan jaringan pasar. Hal ini semakin memberikan harapan bangkitnya perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Namun, kenyataannya memang tidak semua izin PS secara otomatis mendorong terjadi perubahan ekonomi bagi masyarakat. Tidak sedikit izin PS baik itu HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA yang mengalami stagnasi atau tidak ada perubahan dari sebelum adanya izin dan sesudahnya. Keadaan ini bukan berarti karena tidak adanya potensi yang dapat dikembangkan, atau dengan mudah disimpulkan bahwa konsep PS menjadi gagal. Namun lebih pada terbatasnya tenaga pendamping yang dalam kenyataannya memainkan peranan kunci.
Banyak studi menunjukkan dalam sebuah transformasi awal, faktor eksternal yang berperan sebagai stimulus akan memainkan peranan kunci. Pada akhirnya, secara bertahap terjadi transfer pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat.
Lebih dari itu memang peran pendamping sangat diperlukan. Selain menjadi fasilitator masyarakat dalam mengenalkan potensi kekayaan alam di dalam izin PS, dia juga menjadi fasilitator dalam peningkatan keterampilan melalui serangkaian pelatihan dan fasilitator dalam menangkap akses permodalan. Karena begitu besarnya peranan pendamping, maka wajar tidak sedikit pula izin PS yang masih stagnan.
Berangkat dari gambaran di atas, studi ini bermaksud menelaah secara lebih dekat berbagai potensi sumber daya alam baik dari hasil hutan kayu maupun non kayu yang tersimpan dalam kawasan PS. Kajian ini penting sebagai kesimpulan lanjutan dari identifikasi awal mengenai potensi kekayaan yang tersimpan. Tidak hanya menguraikan potensi kekayaan alam semata, lebih dari itu dia juga akan menguraikan potensi pengolahan dan pemasaran. Sehingga sejak awal sudah dapat diidentifikasi nilai ekonomi yang dapat dikembangkan.
Untuk membaca hasil kajian selengkapnya, dapat mendownload naskah kajian di sini:






